"Berarti masalahnya bukan pergi dari orang-orang yang selalu ribut ini-itu, tapi gimana kamu dengar suaramu sendiri di tengah banyaknya suara."
Setelah beberapa hari mengurung di kamar dan gak bisa ngapa-ngapain, rasanya segar banget bisa kembali produktif meski hanya dengan menyelesaikan dan mengulas sebuah buku. Saya akhirnya selesai baca Tokyo dan Perayaan Kesedihan karya Ruth Priscilia ini sore tadi dan jujur, selama baca novelette ini, saya gak bisa berhenti deg-degan. Diri saya seperti terbagi, antara penasaran kepingin tahu secepat mungkin tapi juga takut untuk diberitahu bagaimana akhirnya.
Meski tebakan saya tentang tema novel ini pada awalnya melenceng cukup jauh, ketidaktahuan itulah yang justru membuat saya malah suka banget. Buku ini, buat saya, adalah pembuka bulan April yang sesungguhnya.
Meski tebakan saya tentang tema novel ini pada awalnya melenceng cukup jauh, ketidaktahuan itulah yang justru membuat saya malah suka banget. Buku ini, buat saya, adalah pembuka bulan April yang sesungguhnya.
Tokyo dan Perayaan Kesedihan singkatnya bercerita tentang Shira dan Joshua, dua orang asing dengan kesedihan masing-masing, yang sama-sama bertemu di Jepang. Shira datang ke Tokyo karena merasa butuh waktu untuk dirinya sendiri. Sedangkan motif Joshua, selain untuk mengambil bagian dalam sebuah resital natal, adalah menikmati Jepang setelah diputuskan pacarnya. Keduanya bertemu secara tidak sengaja di airport. Saat itu, Joshua yang sedang tidak enak badan melihat Shira memasukkan Tolak Angin miliknya secara serampangan dan menawarkan untuk membelinya. Pertemuan-pertemuan berikutnya pun terjadi, ada yang sengaja ada yang tidak. Tapi semua itu bermuara pada sebuah perayaan. Perayaan kesedihan.
Hal pertama yang bikin saya jatuh cinta, selain kumpulan foto-foto yang dipakai sebagai pembuka dan penutup setiap bab (yang diambil sendiri oleh penulisnya saat sedang berkunjung ke Tokyo), adalah writing style penulis di buku ini (novelette ini memang buku pertama penulis yang saya baca, tapi saya cukup yakin setelah ini saya bakal tertarik untuk mencoba karya-karyanya yang lain). Setiap kalimat dirangkai dengan sangat cantik. Pemilihan kata di setiap situasi terasa tepat. Saya yang biasanya kurang suka dengan pemakaian "gue" sebagai pengganti "aku" pada sudut pandang orang pertama malah merasa hal itu Shira banget. Shira jelas memiliki ciri khasnya sendiri.
Meski beberapa pertemuan tampak dibuat terlalu sengaja dan "lo-lagi-lo-lagi", saya sangat menikmati setiap percakapan yang terjadi antara Shira dan Joshua. Saya suka Shira yang kadang bawel dan Joshua yang kadang terlalu diam. Saya suka kejujuran Shira tentang perasaan dan keadaannya. Saya suka Joshua yang sedang berusaha untuk menjadi lebih baik. Masalah Joshua dan keluarganya begitu dalam dan menyentuh, saya merasa banyak dari kita yang pasti bisa relate. Di sisi lain, meski hanya "bertemu" sahabat-sahabat Shira lewat cerita singkat Shira saat menulis surat, saya bisa merasakan kedekatan mereka yang realistis dan tidak dibuat-buat. Mulai dari pertengkaran mereka, sayangnya mereka terhadap satu sama lain, dan dukungan yang saling mereka bagi.
Kalau disuruh milih, saya akan bilang saya paling relate sama Shira di buku ini. Apa yang Shira rasakan rata-rata pernah saya rasakan juga, meski mungkin memang konteksnya sedikit berbeda. Dan mengingat bagaimana saya sedang bergumul untuk menemukan diri saya sendiri saat ini, saya merasa konflik di buku ini in a way meresonansikan apa yang sedang saya jalankan. Sulit, tapi memang begitulah hidup. Itulah kenapa saya deg-degan setengah mati untuk Shira. Setengah diri saya ingin yakin kalau Shira akan baik-baik saja, saya pun juga.
Saya juga setuju banget saat Rio, salah satu teman Joshua, mengingatkan kalau mental illness/depresi bukanlah suatu hal yang bisa dianggap remeh dan cuma "main-main". Hal ini sendiri mungkin bukan tema utama dari buku ini, tapi saya merasa poin itu penting sekali. Namun, ada satu pertanyaan saya yang rasanya belum terjawab (tidak bermaksud spoiler, tapi tolong lewati bagian ini kalau kalian belum baca buku ini): Joshua menebak teman terdekat Shira yang "berbeda" adalah Bea dengan pertimbangan satu (atau mungkin beberapa) foto di Instagram. Apa yang membuat Joshua berpikir seperti itu? Kalau saya ada di posisinya, saya mungkin akan memilih untuk menghubungi salah satu teman Shira yang justru pernah Shira ceritakan. Kemungkinan besar sih Edgar. Dan, kalau saya yang ada di posisi Bea, rasanya saya agak takut juga untuk memberi informasi (atau membeberkan rahasia teman) pada orang yang betul-betul asing.
Overall, menurut saya pribadi, buku ini layak banget dibaca. Saya merasa dapat banyak insight baru dari buku ini (dan untuk saat ini, memang hal itulah yang sedang saya cari dari sebuah buku). Selain covernya yang cantik (kece banget gak sih? Saya suka banget lihat designnya), pendeskripsian latar tempatnya yang detail pun gak bikin bosan. Saya merasa seperti ikut berkunjung ke Tokyo selagi mendengar cerita tentang Shira dan Joshua.
Kalau kalian ingin baca sesuatu yang ringan tapi maknanya dalam, buku ini boleh banget dicoba. Sebagai penutup terakhir, saya ingin mengutip kata-kata Shira yang menurut saya pendek tapi ngena banget:
Kalau kalian ingin baca sesuatu yang ringan tapi maknanya dalam, buku ini boleh banget dicoba. Sebagai penutup terakhir, saya ingin mengutip kata-kata Shira yang menurut saya pendek tapi ngena banget:
"... meski dapat disudahi, hidup ini juga berhak dijalani."



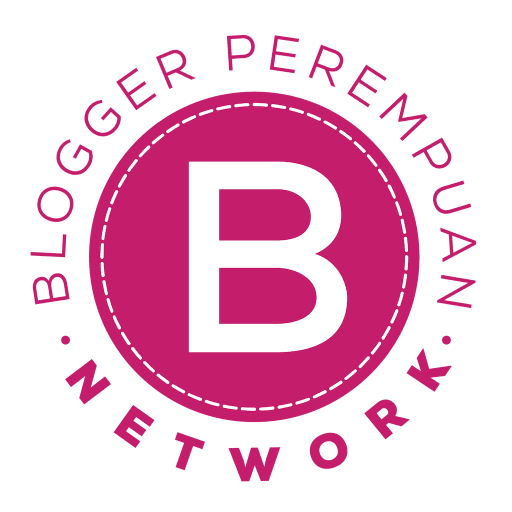













0 Comments